Memori budaya
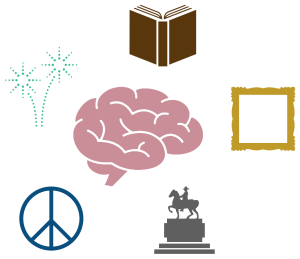 Assmann dan Assmann mendefinisikan ingatan budaya dari perspektif kajian budaya sebagai „tradisi di dalam diri kita, […] teks-teks, gambar, dan ritus-ritus yang telah mengeras dari generasi ke generasi, selama berabad-abad, bahkan dalam beberapa kasus, ribuan tahun, dan yang membentuk kesadaran kita akan waktu dan sejarah, pandangan kita akan diri kita sendiri dan dunia“. (Assmann, J. 2006, 70)
Assmann dan Assmann mendefinisikan ingatan budaya dari perspektif kajian budaya sebagai „tradisi di dalam diri kita, […] teks-teks, gambar, dan ritus-ritus yang telah mengeras dari generasi ke generasi, selama berabad-abad, bahkan dalam beberapa kasus, ribuan tahun, dan yang membentuk kesadaran kita akan waktu dan sejarah, pandangan kita akan diri kita sendiri dan dunia“. (Assmann, J. 2006, 70)
Tiga serangkai memori
Istilah ini, yang digunakan terutama dalam wacana memori dalam kajian budaya, merupakan bagian dari tiga serangkai konseptual yang, menurut Aleida Assmann, menggambarkan bentuk-bentuk memori yang berbeda secara fundamental:
– ingatan individu
– memori komunikatif (sosial)
– memori kultural (bdk. Assmann, A. 2006, 13)
Bentuk-bentuk memori
Sementara ingatan individu seseorang dipenuhi dengan ingatan implisit maupun eksplisit, yaitu ingatan otobiografi, ingatan juga dipertahankan melalui interaksi dengan orang lain dalam ingatan kolektif, yaitu dalam keluarga, dalam kelompok sosial, atau dalam masyarakat secara keseluruhan. Komunikatif, yaitu lisan, tradisi diwariskan dari generasi ke generasi.
Sosiolog Prancis Maurice Halbwachs menggambarkan hubungan antara ingatan individu dan masyarakat sebagai berikut: „Sering kali saya mengingat karena orang lain mendorong saya untuk melakukannya, karena ingatan mereka membantu ingatan saya, karena ingatan saya mengacu pada ingatan mereka. Setidaknya dalam kasus ini, tidak ada yang misterius tentang ingatan“ (Halbwachs 1966, 20).
Namun, „ingatan kita tidak hanya bersifat sosial, tapi juga kultural“ (Assmann, J. 2006, 69). Teks, gambar, benda, simbol, dan ritus membentuk ingatan budaya dan menjadi dasar identitas budaya kita. Pembawa tradisi-tradisi budaya ini adalah „media penyimpanan eksternal dan praktik-praktik budaya“ (Assmann, A. 2006, 19), yang melestarikan bahasa, gambar, suara, dan bunyi. Karena „hanya situs dan media penyimpanan yang mengubah memori komunikatif menjadi memori yang benar-benar kultural.“ (Reichwein 2018)
Sejarah dan identitas
Tetapi bagaimana menentukan apa yang kita ingat dan apa yang kita lupakan? Kalangan AfD menyerukan „perubahan 180 derajat dalam kebijakan mengingat“ dan meminggirkan Holocaust sebagai „sarang burung“. Apa yang disebut „kultus rasa bersalah“ Jerman dikecam dan dengan demikian ingatan kultural semakin dipertanyakan.
Jelaslah bahwa ingatan kultural tidaklah statis. Ia tunduk pada dinamika dan perubahan yang harus didiskusikan dan dinegosiasikan dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena „apa yang diingat dan apa yang dilupakan sebagian besar dibentuk, diorganisir, dan direkonstruksi“ (Reichwein 2018).
Literatur
Assmann, Aleida (2006): Ruang-ruang Memori. Bentuk dan transformasi memori budaya. Cetakan ke-3. Beck: Munich.
Assmann, Jan (2006): Thomas Mann dan Mesir. Mitos dan Monoteisme dalam Novel-novel Joseph. Beck: Munich.
Halbwachs, Maurice (1985): Memori dan kondisi sosialnya. Suhrkamp: Berlin.
Reichwein, Marc (2018): Mengapa tidak ada bangsa yang dapat hidup tanpa ingatan. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article177671164/Nation-und-Erinnerung-So-funktioniert-das-kulturelle-Gedaechtnis.html [13.11.2018].
